Runtuhnya Benteng Moral HMI : 79 Tahun Mengasah Diri dan Menjaga Arah

Oleh : Hasan M. Noer*
JAKARTA, BERITA SENAYAN – Benteng tua di bukit ’kurusetra baksya’ (pertarungan kreativitas) itu, kini bergolak hebat. Jarum sejarah sedang berputar mengantarnya naik ke panggung singgasana. Namun, setelah di atas, tidak ada jalan lain kecuali turun ke lembah ’duli pali’ (pondok tetirah).
Inilah hukum sejarah. Maka merunduk adalah jalan untuk bersandar. Mungkin saja, selalu ada magnet-magnet kecil yang mengganggu, membuat peta arah menjadi kabur. Bukan semata gempuran badai ‘modal eksternal,’ melainkan hunjaman belati ‘moral internal’ sendiri.
Begitulah kiranya HMI hari ini: sebuah organisasi yang lahir dari kejernihan niat dan kegentingan zaman, namun kini kerap diuji oleh tarikan kekuasaan, kemewahan, dan lupa diri.
Di usia 79 tahun—5 Februari 1947 hingga 5 Februari 2026—HMI berdiri di hadapan cermin sejarahnya sendiri: Apakah ia masih menjadi “benteng moral,” atau telah runtuh oleh kepentingan dan kenyamanan?
HMI lahir bukan dari ruang berpendingin, bukan pula dari meja-meja kekuasaan. Ia lahir dari kegelisahan intelektual dan keberanian iman.
Dari Lorong Malioboro, dari denyut revolusi yang belum selesai, dari kesadaran bahwa kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan akhlak adalah kepincangan iman.
Lafran Pane dan generasi awal HMI menanamkan satu keyakinan: mahasiswa Islam harus menjadi penjaga nurani bangsa. Bukan sekadar cerdas, tetapi berkarakter. Bukan hanya terampil, tetapi juga bermoral. Di sinilah posisi moral yang selama ini dirancang bangun oleh HMI.
Karena itu, HMI merumuskan tujuan perkaderannya yang termaktub dalam Lima Kualitas Insan Cita: “Terwujudnya insan akademis, pencipta, pengabdi, bernafaskan Islam, dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridlai Allah SWT.” Sebuah rumusan yang lebih menyerupai ‘janji suci’ daripada sekadar ‘pamflet organisasi.’
Namun, sejarah jarang ramah pada idealisme. Waktu menguji siapa yang setia, siapa pula yang sekadar singgah. Banyak kader dan alumni HMI hari ini menduduki jabatan penting di berbagai lembaga negara: eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN, bahkan pusat-pusat pengambilan keputusan strategis di negeri ini.
Secara angka, ini prestasi. Tetapi secara etika, pertanyaannya jauh lebih getir: Apakah kekuasaan itu masih dipahami sebagai ‘amanah,’ atau telah menjelma menjadi ’via fati’ (jalan takdir)? Apakah jabatan masih dibaca sebagai ladang pengabdian, atau telah berubah menjadi panggung pelesiran, sebagai pintu masuk menuju gaya hidup mewah yang menjauh dari denyut penderitaan rakyat?
Di titik inilah benteng moral itu mulai goyah, bahkan runtuh. Sebagian tokoh dan alumni HMI—tidak semua, tetapi cukup banyak untuk melukai nurani kolektif—terlihat menjauh dari rakyat yang dulu dielu-elukan dalam pidato dan manifesto.
Kini, mereka hidup dalam lingkaran ’privilese,’ larut dalam kemewahan, dan lupa bahwa akar mereka tumbuh dari tanah sederhana, dari rumah-rumah sempit, dari doa ibu-ibu yang berharap anaknya kelak bisa membela nasib rakyat kecil, seperti mereka.
Lebih parah lagi, sadar atau tidak, ada yang ikut menikmati kehidupan yang dibiayai oleh uang korupsi: uang yang dirampas dari hak orang miskin, dari masa depan anak-anak bangsa. Pada saat itu, HMI tidak lagi sekadar kehilangan arah—ia justru terancam kehilangan jiwa.
Sejarah mencatat bahwa kekuasaan tanpa kebajikan hanya akan melahirkan tirani. Dalam Islam, peringatan ini lebih tajam dan transendental. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa, “Setiap pemimpin adalah ‘pemelihara,’ dan setiap pemelihara akan dimintai pertanggungjawabannya.”
Imam Al-Ghazali menyebut penguasa yang rusak sebagai musibah terbesar umat, karena kerusakannya menjalar ke seluruh sendi kehidupan. Kekuasaan, dalam pandangan Islam, bukan puncak kemuliaan, melainkan ujian paling menakutkan bagi iman.
HMI seharusnya berdiri sebagai benteng dari kerusakan itu. Nilai “insan pengabdi” mestinya menundukkan keserakahan. Nilai “bernafaskan Islam” semestinya menyalakan rasa takut kepada Allah dalam setiap kebijakan.
Nilai “tanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur” seharusnya membuat kader HMI alergi terhadap ketimpangan, penindasan, dan korupsi.
Tetapi ketika nilai-nilai ini tinggal sebagai hafalan dalam forum kaderisasi, sementara praktik hidup justru bertolak belakang, maka yang lahir adalah tragedi moral: idealisme di bibir, pragmatisme di tangan.
Inilah kejahatan yang lahir bukan dari niat jahat yang terbesar, melainkan ia hidup dari kebiasaan tunduk pada sistem yang rusak. Banyak alumni HMI menggunakan logika ‘kesempatan dalam kesempitan’ demi memahami pilihan moral ini: sekadar ikhtiar “menyesuaikan diri,” “realistis,” atau “ikut mekanisme” kelembagaan di mana ia berbakti.
Akan tetapi, justru di sanalah letak keruntuhan moral itu. Ketika idealisme dianggap romantisme masa muda, dan pragmatisme dijadikan tanda kedewasaan, maka HMI berhenti menjadi “benteng moral” dan berubah menjadi “ornamen sejarah.”
Padahal, sejarah peradaban selalu mengajarkan hal yang sama. Ibn Khaldun menulis bahwa runtuhnya suatu bangsa bukan karena kekurangan sumber daya, melainkan karena rusaknya akhlak elite-nya.
Ali Syariati mengingatkan bahwa, “Intelektual yang berkhianat pada rakyat, jauh lebih berbahaya daripada penguasa zalim yang intelek.”
Immanuel Kant, filsuf Barat yang terkenal, pernah menegaskan bahwa, “Tindakan bermoral adalah pilihan hidup yang dilakukan karena kewajiban hakiki, bukan karena keuntungan material.”
Karena itu, peringatan 79 tahun HMI seharusnya menjadi momen ‘muhasabah’ yang jujur sekaligus menyakitkan. Bukan sekadar seremonial dan nostalgia, melainkan evaluasi mendasar. Apakah HMI masih melahirkan manusia merdeka yang berani melawan ketidakadilan, atau justru mencetak teknokrat kekuasaan yang bersedia berdamai dengan nuraninya sendiri?
Pertanyaan jauh lebih menyakitkan adalah: Apakah organisasi ini masih menjadi benteng moral bangsa, atau telah berfungsi sebagai jalur legitimasi bagi elite yang lupa akar dan lupa arah? Apakah HMI hari ini, berpihak kepada tokoh dan lembaga, atau masih berpihak pada nilai dan kebenaran?
Tampaknya, arsitek moral HMI hari ini, justru mulai bergeser: ‘membela tokoh dan lembaga, bukan lagi membela nilai dan kebenaran.’ Rupanya, inilah pilihan moral HMI hari ini, seperti diucapkan seorang mantan ketua umum PB HMI yang sedang menikmati manisnya ‘madu kuasa.’
Lafran Pane boleh menggerutu, bahwa benteng moral HMI tidak boleh runtuh oleh kompromi. Ia harus dirawat dengan kritik, diperkuat dengan keteladanan, dan dijaga dengan keberanian. Alumni yang menyimpang harus ditegur, bukan dirayakan.
Kekuasaan harus dikembalikan pada maknanya sebagai amanah, bukan sekadar simbol status. Sebab HMI tidak diukur dari seberapa banyak alumninya berkuasa, melainkan seberapa teguh mereka berdiri di sisi kebenaran.
Di usia ke-79 ini, HMI dipanggil untuk kembali ke jantung nilainya sendiri. Seperti doa para sufi di ujung malam: “Ya Allah, jangan Engkau cabut amanah dari tangan kami, tetapi cabutlah cinta kami pada dunia yang berlebihan.”
Semoga HMI mampu kembali menjadi benteng moral—tempat nurani berlindung, tempat keadilan disemai, dan tempat harapan rakyat dijaga, hingga ridla Allah menjadi tujuan akhir dari setiap langkah. Wallahu a’lam.
*Penulis adalah Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta Periode 1990-1991 dan Wakil Sekjen PB HMI Periode 1992-1994
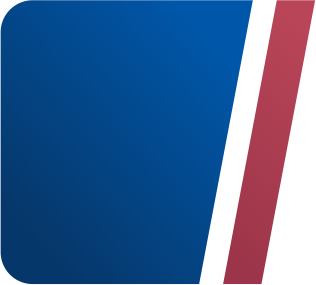 Berita terkait
Berita terkait

Membaca Sulawesi Tenggara Lewat Data: Perbandingan...

Board of Peace: Perdamaian Tanpa Keadilan

Tentang Email antara Jeffrey Epstein dan...

Penerimaan Road Map: Kekalahan atau Kenegarawanan?...

Nalar Hukum KPK dan Warisan Kolonial...

Berjuang Sampai Titik Darah Penghabisan: Amanat...
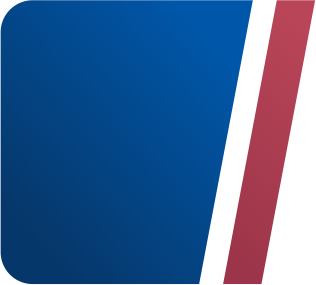 Berita Terbaru
Berita Terbaru

Runtuhnya Benteng Moral HMI : 79...

Rafael Kardinal Tegaskan Komitmen Datangkan Investor...


