Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP 2025: Titik Terang Checks and Balances di Tahap Peradilan

Oleh: Mohammad Arif Nahumbang Harahap*
Hukum tidak hanya berbicara tentang benar dan salah. Ia, pada akhirnya, berbicara tentang cara sebuah negara memperlakukan warganya. Di situlah martabat hukum diuji. Apakah negara hadir hanya sebagai penghukum, atau juga sebagai pemulih? Apakah keadilan dipahami semata sebagai pembalasan, atau sebagai upaya memulihkan luka sosial yang ditinggalkan oleh kejahatan?
Selama puluhan tahun, sistem peradilan pidana Indonesia tumbuh dengan watak yang cenderung retributif. Kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara, dan respons negara hampir selalu berupa pemidanaan. Logika ini membentuk wajah hukum yang tegas, tetapi kerap kering dari dimensi kemanusiaan. Korban sering kali hanya menjadi saksi, pelaku menjadi objek penghukuman, dan masyarakat menerima putusan sebagai akhir dari segalanya. Padahal, konflik sosial tidak selalu selesai di meja hijau.
Di titik inilah keadilan restoratif memperoleh relevansi. Ia lahir dari kesadaran bahwa tindak pidana bukan semata pelanggaran norma, melainkan peristiwa yang merusak relasi antarmanusia. Karena itu, penyelesaiannya tidak cukup dengan menghukum, tetapi harus berupaya memulihkan. Korban perlu ruang untuk didengar, pelaku perlu ruang untuk bertanggung jawab, dan masyarakat perlu jaminan bahwa keseimbangan sosial dapat dipulihkan secara bermartabat.
Indonesia sebenarnya tidak memulai dari nol. Sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif mulai diperkenalkan melalui mekanisme diversi. Pendekatan ini menandai pergeseran penting: anak yang berkonflik dengan hukum tidak lagi semata dipandang sebagai pelaku, tetapi sebagai subjek yang masih memiliki masa depan dan layak dipulihkan. Namun, pengakuan itu masih terbatas. Ia belum menjadi arus utama dalam hukum acara pidana.
Di luar sistem peradilan anak, keadilan restoratif tumbuh melalui kebijakan sektoral. Kepolisian mengaturnya lewat Peraturan Kepolisian, Kejaksaan melalui Peraturan Jaksa Agung, dan Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung. Setiap lembaga melangkah dengan niat baik, tetapi tanpa fondasi bersama dalam undang-undang. Hasilnya adalah praktik yang tidak seragam, bergantung pada kebijakan dan keberanian masing-masing institusi.
Keadilan restoratif pun hidup dalam ruang abu-abu. Di satu daerah ia dijalankan dengan progresif, di daerah lain ia dihindari. Di satu perkara, penghentian perkara dianggap wajar, di perkara lain dianggap menyimpang. Bahkan, pengadilan sering kali tidak pernah tahu bahwa suatu perkara telah diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Penghentian perkara berlangsung tanpa penetapan hakim, tanpa pengawasan yudisial, dan tanpa kepastian hukum yang memadai.
Inilah kelemahan mendasar dari rezim KUHAP lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Di dalamnya tidak ada satu pun pasal yang secara eksplisit mengatur mekanisme keadilan restoratif. Akibatnya, pendekatan ini lebih menyerupai kebijakan administratif ketimbang mekanisme hukum acara pidana yang sahih. Ia bergantung pada diskresi aparat, bukan pada struktur hukum yang baku.
Dalam situasi seperti itu, keadilan restoratif justru mengandung risiko. Ia bisa berubah menjadi jalan pintas untuk menghentikan perkara, bukan sebagai proses pemulihan yang sungguh-sungguh. Korban bisa terpinggirkan, kesepakatan bisa lahir tanpa relasi kuasa yang seimbang, dan negara kehilangan fungsi pengawasannya.
Di sinilah arti penting lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP baru bukan sekadar pembaruan teknis prosedural. Ia membawa pergeseran paradigma. Untuk pertama kalinya, keadilan restoratif diakui secara eksplisit dalam undang-undang sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana.
Pasal 1 angka 21 KUHAP 2025 mendefinisikan keadilan restoratif sebagai pendekatan dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku, dan pihak terkait lainnya, dengan tujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula. Definisi ini sederhana, tetapi mengandung perubahan cara pandang yang mendasar. Negara tidak lagi menempatkan penghukuman sebagai satu-satunya horizon keadilan, melainkan membuka ruang bagi pemulihan sebagai tujuan utama.
Dengan rumusan ini, keadilan restoratif bukan lagi “jalan damai” yang bersifat informal. Ia menjadi bagian dari hukum acara pidana. Ia berdiri sejajar dengan mekanisme penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Negara, melalui undang-undang, mengakui bahwa ada bentuk keadilan yang tidak selalu selesai di dalam penjara.
Pergeseran ini semakin tegas ketika KUHAP 2025 membuka ruang penerapan keadilan restoratif pada seluruh tahapan proses peradilan pidana. Pasal 79 ayat (8) menyebutkan bahwa mekanisme keadilan restoratif dapat dilaksanakan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tidak ada lagi wilayah yang tertutup bagi pemulihan.
Ini bukan perubahan kecil. Ini adalah pernyataan kenegaraan. Negara menyatakan bahwa keadilan restoratif bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan bagian dari wajah resmi peradilan pidana Indonesia.
Namun, pengakuan normatif saja tidak cukup. Tanpa struktur pengawasan yang kuat, keadilan restoratif berpotensi kembali menjadi ruang diskresi sepihak. Karena itu, pertanyaan terpenting berikutnya adalah: siapa yang menjadi penjaga terakhir dari proses ini? Jawabannya ada pada satu kata: pengadilan. Di titik inilah prinsip checks and balances mulai menemukan maknanya yang paling konkret dalam KUHAP 2025.
Jawaban itu menjadi kunci dari seluruh bangunan baru keadilan restoratif dalam KUHAP 2025. Pengadilan ditempatkan sebagai penjaga terakhir. Bukan sekadar lembaga yang mengesahkan putusan, tetapi sebagai institusi yang memastikan bahwa proses pemulihan berjalan adil, setara, dan tidak disalahgunakan.
Selama ini, salah satu kelemahan mendasar penerapan keadilan restoratif terletak pada absennya kontrol yudisial. Penghentian perkara berada sepenuhnya di tangan penyidik atau penuntut umum. Negara, melalui kekuasaan kehakiman, tidak pernah benar-benar hadir untuk menguji apakah kesepakatan damai lahir secara bebas, apakah korban sungguh dilibatkan, dan apakah kepentingan publik tetap terjaga.
KUHAP 2025 mengubah peta itu secara mendasar.
Pasal 79 ayat (5) menegaskan bahwa mekanisme keadilan restoratif harus dituangkan dalam bentuk kesepakatan. Setelah seluruh kesepakatan dilaksanakan, perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan. Kalimat ini tampak sederhana, tetapi maknanya sangat besar. Setiap perdamaian kini harus melewati pintu pengadilan. Tidak ada lagi “damai” yang sah tanpa legitimasi yudisial.
Dengan ketentuan ini, pengadilan tidak lagi berada di pinggir. Ia menjadi decision maker. Ia menjadi penjaga keseimbangan antara kepentingan korban, hak pelaku, dan kepentingan negara. Inilah manifestasi paling konkret dari prinsip checks and balances dalam hukum acara pidana.
Peran itu dipertegas lebih lanjut dalam Pasal 84. Pada tahap penyidikan, penyidik yang menghentikan perkara berdasarkan keadilan restoratif wajib memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. Tidak berhenti di situ, dalam waktu paling lama tiga hari, penyidik juga wajib memintakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Artinya, keputusan penyidik tidak pernah berdiri sendiri. Ia harus diuji secara yudisial.
Hal serupa berlaku pada tahap penuntutan. Pasal 86 menyebutkan bahwa setiap Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan yang diterbitkan berdasarkan keadilan restoratif juga wajib dimintakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri paling lama tiga hari sejak diterbitkan. Penetapan itu kemudian disampaikan kembali kepada penyidik. Rantai koordinasi ini membentuk sistem pengawasan yang saling mengikat.
Di sinilah terlihat bahwa KUHAP 2025 tidak hanya berbicara tentang pemulihan, tetapi juga tentang tata kelola kekuasaan. Tidak ada satu lembaga pun yang memegang kendali penuh. Penyidik, penuntut umum, dan pengadilan saling mengawasi dalam satu sistem yang terhubung.
Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Prim Haryadi, menyebut mekanisme ini sebagai lompatan besar dibanding KUHAP lama. Dalam sistem lama, keadilan restoratif berjalan di luar radar pengadilan. Dalam KUHAP 2025, justru pengadilanlah yang menjadi pusat legitimasi.
Namun KUHAP 2025 juga tidak menutup mata pada risiko penyalahgunaan keadilan restoratif. Karena itu, Pasal 80 ayat (1) memberikan batasan yang tegas. Mekanisme ini hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya paling lama lima tahun penjara atau pidana denda tertentu, dilakukan pertama kali, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali dalam keadaan khusus seperti tindak pidana karena kealpaan.
Pembatasan ini menunjukkan satu sikap penting negara: keadilan restoratif adalah ruang kemanusiaan, tetapi bukan ruang kompromi terhadap kejahatan serius. Ia tidak dimaksudkan untuk mengaburkan kejahatan berat, melainkan untuk menyelesaikan konflik sosial yang masih mungkin dipulihkan secara bermartabat.
Yang menarik, KUHAP 2025 tidak menjadikan keadilan restoratif sebagai pilihan terakhir. Pasal 81 membuka ruang yang luas. Mekanisme ini dapat diajukan oleh pelaku, korban, atau keluarganya. Bahkan, penyelidik, penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat secara aktif menawarkan keadilan restoratif kepada para pihak.
Dengan rumusan ini, negara tidak lagi bersikap pasif. Negara justru mendorong terjadinya pemulihan. Logika hukumnya berubah: bukan menunggu kesepakatan muncul, tetapi memfasilitasi kemungkinan terciptanya kesepakatan.
Lebih jauh lagi, KUHAP 2025 tidak menutup pintu pemulihan di ruang sidang. Pasal 88 menyatakan bahwa apabila keadilan restoratif tidak berhasil dilaksanakan pada tahap penyidikan atau penuntutan, hakim tetap dapat menawarkan mekanisme ini dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Bahkan ketika perkara sudah memasuki ruang persidangan, pemulihan masih dianggap layak diupayakan.
Ini adalah pesan yang sangat kuat. Negara menempatkan pemulihan bukan sebagai pengecualian, melainkan sebagai nilai yang terus diperjuangkan sampai tahap terakhir proses peradilan.
Rangkaian pasal-pasal ini menunjukkan bahwa KUHAP 2025 membangun keadilan restoratif sebagai satu sistem yang utuh: ada definisi, ada ruang penerapan, ada pembatasan, ada mekanisme pengawasan, dan ada legitimasi yudisial.
Namun, sistem yang baik di atas kertas selalu diuji oleh praktik di lapangan. KUHAP 2025 menuntut kesiapan baru dari seluruh aparat penegak hukum. Penyidik harus mampu memfasilitasi dialog yang adil. Penuntut umum harus mampu menilai keseimbangan kepentingan. Hakim harus mampu membaca bukan hanya teks kesepakatan, tetapi juga keadilan di baliknya.
Di titik ini, keadilan restoratif bukan lagi semata persoalan prosedur, melainkan persoalan etika kekuasaan. Ia menuntut kedewasaan aparat hukum untuk menggunakan kewenangan bukan sekadar secara legal, tetapi juga secara bermoral.
Di sinilah tantangan terbesar KUHAP 2025 menunggu. Perubahan paradigma selalu lebih mudah ditulis dalam undang-undang daripada diwujudkan dalam praktik. Keadilan restoratif menuntut perubahan cara berpikir, bukan hanya perubahan prosedur. Ia menuntut aparat penegak hukum untuk keluar dari kebiasaan lama yang menempatkan penghukuman sebagai tujuan akhir, menuju cara pandang baru yang melihat pemulihan sebagai inti keadilan.
Pasal 88 KUHAP 2025 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme keadilan restoratif akan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini penting, sekaligus menjadi titik rawan. Tanpa peraturan pelaksana yang rinci, peran hakim dalam menawarkan, memfasilitasi, dan menilai kesepakatan restoratif bisa berjalan tidak seragam. Di satu pengadilan, ia bisa dipahami secara progresif. Di pengadilan lain, ia bisa berhenti sebagai formalitas administratif.
Padahal, keadilan restoratif tidak hidup dari formulir dan tanda tangan, melainkan dari kualitas dialog, kesetaraan posisi para pihak, dan kejujuran tanggung jawab. Tanpa pedoman teknis yang jelas, risiko terbesarnya adalah keadilan restoratif kembali tereduksi menjadi prosedur, bukan proses kemanusiaan.
Ke depan, Peraturan Pemerintah tentang Mekanisme Keadilan Restoratif akan menjadi kunci. Ia bukan sekadar pelengkap KUHAP, tetapi penentu arah keberhasilan seluruh sistem. Peraturan ini harus mampu mengharmoniskan berbagai regulasi sektoral yang selama ini berdiri sendiri, seperti Peraturan Kepolisian, Peraturan Jaksa Agung, dan Peraturan Mahkamah Agung. Negara tidak lagi memerlukan banyak rezim keadilan restoratif yang berjalan paralel. Yang dibutuhkan adalah satu sistem terpadu, dengan standar yang sama dari hulu sampai hilir.
Jika harmonisasi itu terwujud, KUHAP 2025 akan menandai satu fase baru dalam sejarah peradilan pidana Indonesia. Untuk pertama kalinya, keadilan restoratif tidak hanya menjadi wacana kemanusiaan, tetapi menjadi mekanisme negara yang utuh, terstruktur, dan berada di bawah pengawasan kekuasaan kehakiman.
Dalam perspektif ketatanegaraan, ini adalah penguatan penting terhadap prinsip pemisahan kekuasaan. Penegakan hukum tidak lagi didominasi oleh kekuasaan eksekutif melalui kepolisian dan kejaksaan, tetapi dikontrol secara aktif oleh kekuasaan yudikatif. Pengadilan tidak lagi sekadar menjadi “penerima berkas perkara”, melainkan penjaga keseimbangan kewenangan antar lembaga.
Pada saat yang sama, KUHAP 2025 memperlihatkan wajah hukum yang lebih manusiawi. Negara mengakui bahwa keadilan tidak selalu identik dengan penderitaan pelaku, tetapi dapat hadir melalui tanggung jawab, pengakuan kesalahan, dan pemulihan korban. Di sinilah hukum bertemu dengan martabat manusia.
Tentu saja, keadilan restoratif bukan jawaban untuk semua perkara. Karena itu, pembatasan jenis tindak pidana dalam Pasal 80 menjadi fondasi penting. Negara secara sadar membedakan antara kejahatan yang masih mungkin dipulihkan secara sosial dan kejahatan yang menuntut respons represif demi perlindungan masyarakat luas. Keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk melemahkan hukum pidana, melainkan untuk menyempurnakannya.
Keseimbangan inilah yang menjadi inti dari KUHAP 2025. Di satu sisi, ia membuka ruang kemanusiaan. Di sisi lain, ia tetap menjaga ketegasan negara hukum. Pemulihan dan kepastian hukum tidak dipertentangkan, tetapi ditempatkan dalam satu tarikan napas.
Jika kelak KUHAP 2025 berhasil dijalankan dengan konsisten, maka ia bukan hanya menjadi pembaruan hukum acara, tetapi menjadi tonggak peradaban hukum. Ia menunjukkan bahwa negara ini tidak lagi memandang warganya semata sebagai objek penegakan hukum, melainkan sebagai manusia yang martabatnya harus dipulihkan ketika hukum bekerja.
Pada akhirnya, mekanisme keadilan restoratif dalam KUHAP 2025 membawa satu pesan kenegaraan yang jernih:
negara tidak lagi berdiri hanya sebagai penghukum, tetapi juga sebagai pemulih. Peradilan tidak lagi hanya berbicara tentang siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi tentang bagaimana luka sosial bisa disembuhkan secara adil dan bermartabat. Dan di situlah checks and balances menemukan maknanya yang paling dalam: bukan sekadar pengawasan antar lembaga, melainkan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanusiaan.
*Penulis adalah Praktisi Hukum
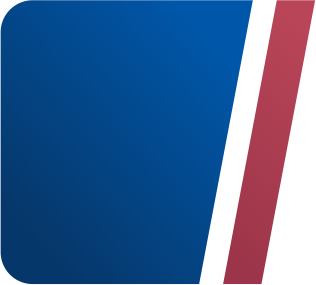 Berita terkait
Berita terkait

Paradoks Khamenei: Imam Tertinggi Revolusi Penggemar...

Obituari John Tobing Pencipta Lagu Darah...

Bahlil Orang Pande : Perspektif Tasawuf

Setahun ASR–Hugua: Membaca Arah Tata Kelola...

Runtuhnya Benteng Moral HMI : 79...

Membaca Sulawesi Tenggara Lewat Data: Perbandingan...
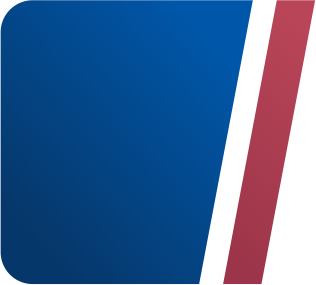 Berita Terbaru
Berita Terbaru

Menutup Rangkaian Ramadhan, FOSTA FPG DPR...

Paradoks Khamenei: Imam Tertinggi Revolusi Penggemar...



