Krisis Legitimasi, Runtuhnya Kelas Menengah, dan Negara yang Tak Mau Bercermin
Rabu, 01 Oktober 2025, 19:54:25 WIB

Oleh: Airlangga Pribadi Kusman*
Di tengah hiruk-pikuk politik pasca-Agustus, kita menyaksikan negara kembali menggunakan resep lama untuk menghadapi protes rakyat: represi. Aktivis ditangkap, demonstrasi dihadang, dan suara-suara kritis dibungkam. Namun yang menarik, pola represi ini muncul justru ketika keresahan sosial semakin nyata, ketika rakyat—khususnya kelas menengah—jatuh ke titik terendah dalam sejarah pembangunan pascareformasi.
Alih-alih berusaha memahami, negara seolah menolak bercermin. Padahal, cermin itu menunjukkan retakan mendasar dalam fondasi sosial-ekonomi bangsa: ketimpangan struktural yang semakin lebar, pemiskinan kelas menengah, serta kegagalan elite politik menyalurkan aspirasi rakyat. Cermin itu dibanting, sementara realitas pahit tetap ada.
Mengapa krisis sosial ini meletus? Bagaimana negara salah membaca tanda zaman, dan apa risiko besar yang menunggu bila akar persoalan ini tidak segera ditangani? Salah satu fondasi stabilitas politik di negara demokrasi modern adalah keberadaan kelas menengah yang kuat. Kelas menengah berperan sebagai penyangga—menjadi motor mobilitas sosial, konsumen yang menopang ekonomi, sekaligus basis bagi demokrasi partisipatif.
Namun dalam lima tahun terakhir (2019–2024), fondasi ini ambruk dengan cepat. Data menunjukkan sekitar 9 juta jiwa terperosok dari kelas menengah ke kelas bawah. Angka ini bukan sekadar statistik kering; ia menyimpan cerita manusiawi tentang degradasi hidup. Seorang manajer perusahaan yang terkena PHK kini menjadi pengemudi ojek online. Seorang keluarga yang dulu optimistis bisa menyekolahkan anaknya hingga universitas, kini harus berhutang karena biaya UKT di kampus negeri pun kian mencekik.
Fenomena ini disebut sebagai deprivasi relatif—jurang antara ekspektasi hidup lebih baik dengan realitas pahit yang dihadapi. Ekspektasi yang lahir dari pendidikan, kerja keras, dan janji pembangunan ternyata berhadapan dengan stagnasi, bahkan kemunduran. Ketika pendapatan menurun, biaya hidup meningkat, dan akses terhadap layanan dasar semakin diprivatisasi, perasaan kehilangan ini meledak menjadi kekecewaan sosial.
Kekecewaan itu tidak berhenti di ruang privat keluarga. Ia menjelma menjadi gerakan sosial. Aksi buruh, mahasiswa, hingga gelombang solidaritas pengemudi ojol adalah bentuk artikulasi politik rakyat yang absah.
Kasus tragis Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas ditabrak, menjadi pemicu solidaritas luas. Ribuan pengemudi ojol turun ke jalan, bukan sekadar menuntut keadilan individual, tetapi meluapkan frustrasi kolektif tentang betapa rapuhnya posisi sosial mereka.
Namun, inilah titik belok: ekspresi politik yang seharusnya diterima negara sebagai alarm justru dianggap sebagai ancaman. Aparat bergerak dengan logika represi. Aktivis seperti Delpedro Marhaen, yang memberi advokasi hukum bagi pelajar ditangkap, dan Paul dari Social Movement Institute, yang aktif mendampingi gerakan sosial, juga ditahan. Padahal, mereka bukan kriminal. Mereka adalah bagian dari masyarakat sipil yang mencoba mengisi kekosongan kanal politik formal yang gagal menyerap aspirasi rakyat.
Di sinilah ironi demokrasi Indonesia: ketika kanal formal seperti partai politik dan parlemen lumpuh sebagai saluran aspirasi, masyarakat sipil justru menjadi target represi. Negara menolak memahami akar persoalan yang sesungguhnya: runtuhnya kelas menengah dan semakin lebarnya ketimpangan sosial.
Alih-alih membuka ruang dialog, elite justru larut dalam konsensus internal. Politik direduksi menjadi negosiasi sesama elite, bukan kontrak sosial dengan rakyat. Dalam bahasa metaforis: cermin yang menunjukkan retakan sosial itu dibanting. Negara menolak bercermin, memilih mengabaikan realitas, padahal luka sosial semakin membesar.
Jürgen Habermas, filsuf Jerman, sejak 1970-an telah mengingatkan tentang bahaya krisis legitimasi. Dalam bukunya Legitimation Crisis (1973), ia menjelaskan bahwa masyarakat kapitalis modern rentan mengalami krisis ketika institusi negara gagal mengatasi ketidakpuasan ekonomi dan tidak lagi dipercaya oleh warganya.
Krisis legitimasi bukan sekadar soal jatuhnya angka pertumbuhan ekonomi, melainkan runtuhnya kepercayaan rakyat pada negara. Habermas menyebut ini sebagai benturan antara “sistem” (negara, pasar, birokrasi) dengan “lifeworld” (dunia kehidupan sehari-hari warga, norma sosial, ekspektasi hidup).
Dalam konteks Indonesia, benturan itu terlihat jelas:
* Sistem berwujud klaim elite tentang kemajuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik.
* Lifeworld berwujud kenyataan pahit: biaya hidup meningkat, pendidikan mahal, lapangan kerja menyempit, dan status sosial menurun.
Ketika rakyat melihat ketidakcocokan antara klaim elite dan realitas hidup, kepercayaan pun runtuh. Inilah krisis legitimasi yang mulai membayangi.
Fenomena runtuhnya kelas menengah bisa dilihat dari melonjaknya jumlah pengemudi ojek online. Data BPJS menyebut ada sekitar 2 juta ojol; sementara perusahaan swasta seperti Maxim memperkirakan jumlahnya mencapai 5–7 juta. Dari angka itu, 1,7 juta lebih tidak memiliki perlindungan sosial.
Di satu sisi, ojol menjadi simbol fleksibilitas ekonomi digital. Namun di sisi lain, ia adalah simbol kemunduran kelas menengah. Orang-orang yang dulu hidup mapan, kini terjun ke sektor informal yang rapuh. Mobilitas sosial vertikal terbalik: dari kelas menengah ke kelas rentan.
Privatisasi pendidikan dan layanan publik memperparah kondisi ini. Biaya kuliah di universitas negeri pun melonjak, memaksa banyak keluarga kelas menengah untuk berhutang. Sementara upah stagnan, daya beli melemah, dan harga kebutuhan pokok terus naik.
Dalam sejarah politik modern, kelas menengah yang hancur kerap menjadi sumber instabilitas politik. Karena mereka adalah kelompok yang paling vokal, paling sadar, dan paling kecewa ketika janji pembangunan tidak terpenuhi.
Penangkapan aktivis dan represi terhadap demonstrasi mungkin terlihat efektif dalam jangka pendek. Namun dalam perspektif sosiologi politik, represi hanyalah jalan pintas yang mempercepat runtuhnya legitimasi negara.
Dengan membungkam masyarakat sipil, negara menutup satu-satunya kanal yang tersisa bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Akibatnya, ketidakpuasan justru menumpuk tanpa saluran. Seperti gunung berapi, tekanan itu suatu saat bisa meledak lebih dahsyat.
Sejarah membuktikan: rezim yang menolak mendengarkan rakyat pada akhirnya berhadapan dengan krisis legitimasi yang tidak bisa mereka kendalikan. Padahal, jalan keluar sudah ditawarkan oleh masyarakat sipil. Agenda 17+8 yang disuarakan gerakan sosial adalah upaya konkret untuk mengembalikan kesehatan demokrasi dan sistem politik kita.
Agenda itu bukan sekadar tuntutan jalanan, melainkan paket solusi politik yang lahir dari keresahan rakyat. Namun sayangnya, elite tidak pernah serius merespons. Elite lebih sibuk meramu konsensus internal, sementara rakyat hanya dijadikan penonton.
Kegagalan merespons agenda ini menandakan bahwa negara sedang kehilangan arah: tidak mampu melihat peluang dialog yang bisa meredam krisis sejak dini.
Indonesia bukan satu-satunya negara yang menghadapi krisis legitimasi. Nepal, misalnya, mengalami gelombang protes besar ketika rakyat merasa demokrasi tidak lagi menjawab kebutuhan mereka. Di banyak negara Amerika Latin, krisis ekonomi yang meruntuhkan kelas menengah berujung pada keruntuhan legitimasi politik.
Pelajarannya jelas: ketidakpercayaan rakyat adalah racun paling mematikan bagi negara demokrasi. Demokrasi hanya bisa bertahan jika rakyat percaya bahwa suara mereka didengar, aspirasi mereka diakomodasi, dan negara bekerja untuk kepentingan publik, bukan elite.
Indonesia kini berada di persimpangan. Apakah negara akan terus membanting cermin—menolak melihat realitas sosial yang pahit—atau berani bercermin, mengakui retakan, dan memperbaikinya?
Menangkap aktivis dan membungkam demonstrasi bukanlah solusi. Itu hanya cara menunda krisis, yang pada akhirnya membuat legitimasi runtuh lebih cepat.
Jika pemerintah ingin menjaga stabilitas politik, ia harus mengambil langkah berani:
* Mengakui realitas runtuhnya kelas menengah dan krisis sosial yang menyertainya.
* Membuka dialog dengan masyarakat sipil, bukan menutupnya dengan represi.
* Menjawab agenda rakyat seperti 17+8 secara konkret, bukan dengan janji kosong.
* Mereformasi kanal politik agar partai dan parlemen kembali menjadi saluran aspirasi rakyat.
Demokrasi berangkat dari kedaulatan rakyat. Tanpa kepercayaan rakyat, negara hanyalah bangunan kosong. Sejarah mengingatkan: rezim yang gagal bercermin akan dihancurkan oleh bayangan mereka sendiri.
*Penulis adalah dosen Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) dan Direktur Eksekutif CSCS (Centre of Statecraft and Citizenship Studies) Fisip Universitas Airlangga.
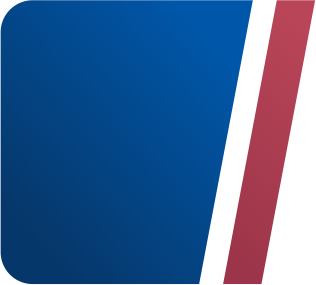 Berita terkait
Berita terkait

Menopang Ekonomi Indonesia di 2026 :...

Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP 2025:...

Merangkai Luka, Mematahkan Sunyi: Membaca Broken...

Tas Oranye di Kampung yang Gelap

Penolakan Gen Z atas Pilkada DPRD...

Indonesia di Persimpangan Sistem Pemilu?
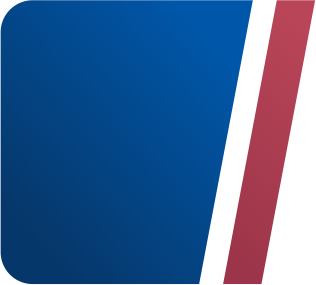 Berita Terbaru
Berita Terbaru

Menopang Ekonomi Indonesia di 2026 :...

Hetifah Sjaifudian: Anggaran Khusus Bencana Wajib...



