Board of Peace: Perdamaian Tanpa Keadilan

Oleh : Suhermanto Ja’far
JAKARTA, BERITA SENAYAN – Board of Peace lahir bukan dari ruang hampa moral, melainkan dari lanskap geopolitik global yang sarat krisis legitimasi. Inisiatif ini muncul di tengah kelelahan dunia terhadap konflik berkepanjangan, terutama di Timur Tengah, sekaligus kegagalan komunitas internasional menegakkan keadilan substantif bagi Palestina. Di permukaan, Board of Peace dipresentasikan sebagai proyek etis universal—dialog lintas agama, moderasi, dan stabilitas global. Namun, di balik narasi damai tersebut, tersimpan kepentingan geopolitik yang tidak netral: meredam konflik tanpa menyentuh akar kolonialisme dan ketimpangan kekuasaan yang melahirkannya.
Contradicitio in terminis
Mens area Board of Peace tidak dapat dilepaskan dari warisan politik luar negeri Donald Trump. Di bawah slogan stabilitas dan pragmatisme, Trump menggeser paradigma perdamaian dari keadilan menuju transaksi. Kesepakatan Abraham Accords menjadi preseden penting: normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel dipromosikan sebagai “perdamaian”, meskipun pendudukan dan penindasan terhadap Palestina tetap berlangsung. Dalam kerangka ini, perdamaian tidak lagi dipahami sebagai pembebasan dari kolonialisme, melainkan sebagai manajemen konflik agar tidak mengganggu kepentingan strategis Amerika Serikat dan sekutunya.
Israel menjadi aktor yang paling diuntungkan dari desain Board of Peace semacam ini. Dengan mengedepankan dialog dan moderasi, isu Palestina direduksi dari persoalan kolonialisme menjadi sekadar konflik antar-pihak yang “sama-sama bermasalah”. Board of Peace menyediakan legitimasi moral baru: Israel tidak perlu mengakhiri pendudukan, cukup hadir dalam forum perdamaian global dan membiarkan dunia Islam sibuk merayakan stabilitas. Dalam skema ini, kekerasan struktural dilapisi bahasa etika, dan penindasan dilegitimasi atas nama harmoni.
Di sinilah dilema etis Indonesia bermula. Ketika Indonesia—negara yang secara konstitusional menolak segala bentuk penjajahan—masuk ke dalam arsitektur Board of Peace, pertanyaannya bukan sekadar soal kehadiran, melainkan posisi moral. Apakah Indonesia hadir sebagai suara keadilan, atau justru menjadi bagian dari panggung yang menormalisasi ketidakadilan? Board of Peace, dengan seluruh jargon damainya, menempatkan Indonesia pada persimpangan krusial: antara mempertahankan etika politik luar negeri yang berakar pada keadilan Palestina, atau terjebak dalam perdamaian global yang tenang di permukaan, namun timpang di dasar.
Konteks ini tidak dapat dilepaskan dari peace framework era Donald Trump. Inisiatif perdamaian yang lahir pada masa tersebut—termasuk logika Abraham Accords—mendefinisikan perdamaian sebagai normalisasi hubungan dan stabilitas kawasan, bukan sebagai penghapusan pendudukan dan kolonialisme Israel atas Palestina (Mearsheimer 2018, 30–34).
Dalam kerangka ini, Palestina tidak diposisikan sebagai bangsa yang dijajah, melainkan sebagai variabel pengganggu stabilitas. Konflik direduksi menjadi persoalan dialog dan koeksistensi, sementara akar kolonialisme dan kekerasan struktural dikesampingkan (Khalidi 2020, 93–97).
Indonesia dan Dilema Etis
Di sinilah inti masalahnya. Persoalan utama bukan pada kehadiran Indonesia atau Suara “pengurus” PBNU yanag mendukungnya dalam forum global, melainkan kehadiran tanpa posisi tegas terhadap kolonialisme Israel. Ketika Indonesia dan NU duduk di ruang yang menormalisasi status quo, netralitas berubah menjadi partisipasi pasif dalam ketidakadilan.
Jika Palestina hanya dibela secara retoris—melalui pernyataan moral dan bantuan kemanusiaan—sementara pada saat yang sama forum internasional yang diikuti justru mengaburkan status Israel sebagai occupying power, maka yang terjadi bukan keseimbangan diplomatik, melainkan normalisasi penindasan (Pappé 2017, 45–49).
Dilema ini nyata bagi Indonesia. Di satu sisi, Indonesia ingin menjaga peran sebagai aktor moderat, bridge builder, dan negara berpolitik luar negeri bebas aktif. Di sisi lain, struktur geopolitik global sering memaksa kompromi narasi agar tetap “diterima” dalam arsitektur perdamaian yang dikendalikan kekuatan besar (Chomsky 2016, 61–64).
NU pun menghadapi dilema serupa. Niatnya untuk menjaga perdamaian, menghindari konflik terbuka, dan menyuarakan Islam moderat berhadapan dengan risiko kehilangan daya kritis. Moderasi yang tidak disertai keberpihakan pada korban kolonialisme berpotensi menjadi etika tanpa daya politik (Richmond 2016, 22–25).
Sikap yang lebih etis dan konsisten bukanlah menarik diri dari diplomasi global, melainkan terlibat dengan posisi yang jelas. Keterlibatan harus disertai penegasan bahwa Israel adalah kekuatan pendudukan, bahwa Palestina memiliki hak menentukan nasib sendiri, dan bahwa normalisasi tanpa keadilan adalah bentuk pengingkaran moral.
Pendekatan ini menuntut keberanian politik. Indonesia dan NU harus mampu menolak kerangka perdamaian yang memisahkan stabilitas dari keadilan. Perdamaian yang menuntut korban untuk diam bukanlah perdamaian, melainkan pengelolaan konflik demi kepentingan hegemonik (Acharya 2018, 18–20).
Edward Said pernah mengingatkan bahwa “peace without justice is merely the silence of the oppressed.” Perdamaian tanpa keadilan hanyalah keheningan yang dipaksakan kepada mereka yang ditindas, sementara dunia menikmati stabilitas semu (Said 2001, 67–69).
Dalam konteks ini, Board of Peace ala Trump lebih tepat dibaca sebagai proyek stabilitas imperialis. Ia tidak bertujuan membebaskan Palestina, tetapi menenangkan kawasan agar selaras dengan kepentingan strategis Amerika dan keamanan Israel (Mearsheimer 2018, 35–37).
Indonesia dan NU tidak dapat sepenuhnya disalahkan. Keduanya berniat normatif dan damai. Namun niat baik tidak cukup ketika struktur global bekerja secara asimetris. Tanpa sikap kritis, niat baik justru berisiko dimanfaatkan untuk memberi legitimasi moral pada ketidakadilan yang sedang berlangsung.
Pada akhirnya, Palestina tetap menjadi korban dari perdamaian palsu. Jika Indonesia dan NU ingin menjaga kedaulatan moralnya, maka keberanian untuk bersikap tegas terhadap penindasan Israel adalah syarat mutlak. Tanpa itu, perdamaian hanya menjadi nama lain dari ketertiban yang menindas (*)
*Penulis adalah Dosen Filsafat Digital Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya
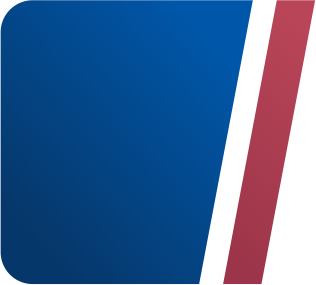 Berita terkait
Berita terkait

Tentang Email antara Jeffrey Epstein dan...

Penerimaan Road Map: Kekalahan atau Kenegarawanan?...

Nalar Hukum KPK dan Warisan Kolonial...

Berjuang Sampai Titik Darah Penghabisan: Amanat...

KPK, Nalar Silo Digital Hukum dan...

Jokowi dalam Pusaran Isu Korupsi Kuota...
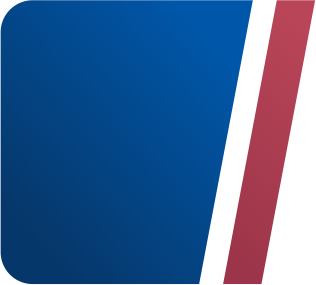 Berita Terbaru
Berita Terbaru

Board of Peace: Perdamaian Tanpa Keadilan

Siswa Gantung Diri di NTT, Atalia...


