KPK, Nalar Silo Digital Hukum dan Diskresi Kuota Haji

*Oleh : Suhermanto Ja’far
JAKARTA, BERITA SENAYAN – Kasus Kuota Haji tidak hanya menguji mekanisme hukum pidana, tetapi juga menguji cara bernalar lembaga penegak hukum di era digital. Di tengah sorotan publik yang intens, persoalan ini memperlihatkan satu problem mendasar: penyempitan cara membaca kebijakan publik akibat nalar yang terjebak dalam apa yang disebut silo digital. Dalam kondisi ini, hukum berisiko bekerja dalam ruangnya sendiri, terpisah dari realitas kemanusiaan yang justru melahirkan kebijakan.
Silo digital merujuk pada situasi ketika aktor—baik individu maupun institusi—beroperasi dalam ruang informasi dan logika yang terfragmentasi. Setiap persoalan dibaca melalui satu lensa disipliner, tanpa dialog serius dengan pengetahuan lain. Dalam konteks Kuota Haji, kecenderungan ini tampak ketika hukum dibaca semata-mata melalui teks aturan, prosedur administratif, dan potensi pelanggaran normatif, tanpa integrasi dengan disiplin lain yang relevan.
Padahal, kebijakan haji adalah kebijakan kompleks yang menyentuh dimensi manajemen kerumunan, keselamatan publik, diplomasi internasional, etika kebijakan, hingga teologi kemanusiaan. Risiko kematian jamaah, kepadatan ekstrem di Mina dan Arafah, serta pengalaman empiris musim haji sebelumnya bukan sekadar latar belakang, melainkan inti dari pertimbangan kebijakan. Ketika dimensi ini diabaikan, hukum kehilangan konteksnya.
Akibat dari silo digital tersebut, kebijakan yang lahir dari pertimbangan lintas-disiplin direduksi menjadi deviasi prosedural. Keselamatan jiwa, yang semestinya menjadi tujuan utama, tenggelam di bawah pembacaan normatif yang kaku. Hukum seolah berdiri sendiri, terlepas dari realitas sosial yang dimediasi oleh teknologi, data kepadatan, dan risiko kemanusiaan. Inilah titik rapuh penegakan hukum di era kompleksitas digital.
Masalah ini diperparah oleh framing digital yang bekerja agresif di ruang publik. Dalam ekosistem media sosial dan YouTube, isu Kuota Haji tidak disajikan sebagai persoalan kebijakan darurat, melainkan disederhanakan menjadi narasi moral hitam-putih: “tambahan kuota sama dengan peluang korupsi.” Algoritma digital mendorong narasi konflik, personalisasi, dan tuduhan, bukan analisis kebijakan.
Framing semacam itu secara perlahan menggiring persepsi publik. Diskresi kebijakan dibaca sebagai niat jahat, sementara pejabat publik diposisikan sebagai “tersangka moral” bahkan sebelum proses hukum berjalan. Konteks keselamatan jamaah, pengalaman kematian tahun-tahun sebelumnya, dan kompleksitas teknis haji tersingkir oleh logika viralitas. Publik akhirnya menghakimi lebih cepat daripada hukum bekerja.
Tekanan opini digital ini tidak bisa dianggap remeh. Ia menciptakan beban simbolik bagi lembaga penegak hukum, termasuk KPK, untuk bergerak sesuai ekspektasi publik digital. Ketika hukum mulai merespons tekanan algoritmik, bukan pembacaan utuh atas konteks kebijakan, maka hukum berisiko bergeser dari instrumen keadilan menjadi instrumen konfirmasi kemarahan kolektif.
Di titik inilah kebutuhan akan perubahan paradigma menjadi mendesak. Nalar hukum tidak cukup lagi bertumpu pada pendekatan silo. Era digital menuntut apa yang dapat disebut sebagai paradigma polymath digital—kemampuan membaca satu persoalan dengan banyak lensa sekaligus: hukum, etika, data, risiko, dan kemanusiaan. Tanpa itu, hukum akan selalu tertinggal dari kompleksitas realitas.
Paradigma polymath digital menuntut hukum untuk berdialog dengan disiplin lain. Hukum tidak hanya bertanya “apakah prosedur dilanggar?”, tetapi juga “apa konsekuensi kebijakan terhadap nyawa manusia?”, “apa pelajaran empiris dari pengalaman sebelumnya?”, dan “apa justifikasi etis dalam situasi darurat?”. Dengan cara ini, hukum tidak kehilangan ketegasannya, tetapi justru memperdalam rasionalitasnya.
Jika kasus Kuota Haji dibaca dengan nalar polymath digital, maka diskusi tidak berhenti pada angka dan regulasi. Ia bergerak pada evaluasi risiko kematian jamaah jika kuota dibagi tidak proporsional, keterbatasan infrastruktur di lapangan, serta tanggung jawab negara untuk mencegah tragedi kemanusiaan. Di sini, diskresi kebijakan dipahami sebagai upaya rasional, bukan otomatis sebagai indikasi kriminalitas.
Peralihan dari silo digital ke polymath digital bukan berarti melemahkan penegakan hukum. Sebaliknya, ia justru memperkuat legitimasi hukum. Hukum yang mampu membaca konteks akan lebih dipercaya publik dibanding hukum yang hanya mengutip pasal. KPK, sebagai institusi strategis, justru akan tampil lebih berwibawa jika menunjukkan kapasitas analitis lintas-disiplin, bukan sekadar keberanian prosedural.
Pada akhirnya, kasus Kuota Haji adalah cermin bagi nalar hukum kita di era digital. Apakah hukum akan terus bekerja dalam silo yang sempit, atau berani bergerak menuju cara berpikir polymath yang lebih utuh dan manusiawi? Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya menentukan nasib satu kasus, tetapi juga menentukan apakah hukum kita sanggup menjaga keadilan di tengah kompleksitas peradaban digital yang semakin menantang.
*Penulis adalah Dosen Filsafat Digital Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya
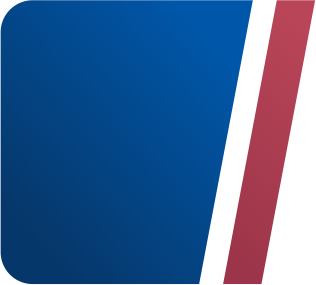 Berita terkait
Berita terkait

Penerimaan Road Map: Kekalahan atau Kenegarawanan?...

Nalar Hukum KPK dan Warisan Kolonial...

Berjuang Sampai Titik Darah Penghabisan: Amanat...

Jokowi dalam Pusaran Isu Korupsi Kuota...

Membaca Posisi Indonesia di Dewan Perdamaian...

Mantan Menag Dijerat Kasus Kuota Haji:...
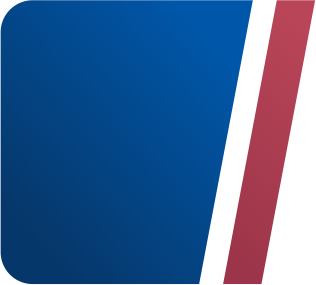 Berita Terbaru
Berita Terbaru

Habib Syarief: Kemendikdasmen Harus Usut Tuntas...

Kaisar Abu Hanifah: Bonus Demografi Terancam...



