Penerimaan Road Map: Kekalahan atau Kenegarawanan? Membaca Dinamika Konflik PBNU

Oleh : Suhermanto Ja’far*
Penerimaan road map yang ditawarkan Rais Aam oleh Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, segera memantik perdebatan di kalangan warga NU. Sebagian membacanya sebagai bentuk kekalahan politik, sebagian lain menilainya sebagai sikap kenegarawanan. Perdebatan ini wajar, sebab dalam organisasi besar seperti PBNU, satu tindakan yang sama bisa mengandung makna ganda—tergantung dari sudut pandang yang digunakan (March & Olsen 1989, 21–23).
Tulisan ini akan mencoba untuk membaca dinamika konflik yang terjadi dan tidak pretensi melakukan pembelaan individual ataupun ketidak sukaan secara personal kepada pengurus PBNU. Tulisan ini berusaha untuk menganalisis secara sosiologi digital melihat fenomena perilaku netizen dalam ruang digital khususnya medsos khususnya grup grup Whatapps (Lupton 2015, 8–11; Couldry 2012, 57–59).
Jika dibaca secara sosiologis dan institusional, penerimaan road map tersebut tidak bisa disederhanakan sebagai kekalahan personal. Gus Yahya sejak awal konsisten menolak pemecatan terhadap dirinya karena dinilai tidak sesuai dengan AD/ART. Posisi ini tidak pernah dicabut, bahkan setelah road map diterima. Artinya, tidak ada pengakuan kesalahan struktural yang disampaikan secara formal (Selznick 1949, 65–68).
Dalam logika organisasi, menerima road map lebih tepat dipahami sebagai upaya memindahkan konflik dari wilayah eskalasi personal ke wilayah pengelolaan kelembagaan. Ini sejalan dengan konsep conflict containment dalam teori kepemimpinan, di mana pemimpin memilih menahan konflik terbuka demi menjaga stabilitas organisasi, tanpa harus menyerah pada substansi yang dipersoalkan (Heifetz 1994, 103–107).
Namun demikian, tindakan ini tetap membawa risiko simbolik. Dalam politik internal organisasi, simbol sering kali lebih kuat daripada substansi. Penerimaan road map dengan mudah ditafsirkan sebagai sikap “mengalah”, terutama oleh mereka yang melihat konflik ini sebagai pertarungan otoritas antara Rais Aam dan Ketua Umum PBNU (Edelman 1988, 12–15).
Pertanyaan kunci yang perlu diajukan adalah: apakah penerimaan road map ini didasarkan pada pertimbangan kepentingan jami’iyah dan kelembagaan PBNU, ataukah semata-mata strategi personal untuk meredam tekanan? Di sinilah ukuran kenegarawanan diuji—bukan pada gestur menerima, tetapi pada orientasi dan dampak tindak lanjutnya (Weber 1978, 225–227).
Pleno PBNU yang kemudian berujung pada ishlah memperlihatkan adanya kehendak kolektif untuk mengakhiri konflik terbuka. Secara normatif, ishlah adalah nilai luhur dalam tradisi NU. Namun dalam praktik organisasi modern, ishlah yang tidak diiringi kejelasan prosedural sering kali hanya menjadi penutup konflik sementara (Coser 1956, 154–156).
Penerimaan maaf oleh Rais Aam atas apa yang disebut sebagai “kesalahan-kesalahan Gus Yahya”, dan sebaliknya penerimaan maaf Ketua Umum oleh Rais Aam, secara simbolik memang menyejukkan. Akan tetapi, secara struktural, penerimaan maaf tidak otomatis menjawab pertanyaan mendasar tentang batas kewenangan, mekanisme pengambilan keputusan, dan disiplin organisasi (Luhmann 2004, 142–145).
Di titik ini, muncul pertanyaan kritis: apakah ishlah dan permohonan maaf tersebut benar-benar lahir dari kesadaran demi kepentingan jami’iyah, sebagaimana saran para kiai sepuh, ataukah lebih bersifat simbolik untuk memulihkan citra yang telah terlanjur tercoreng di ruang publik? Jawaban atas pertanyaan ini tidak bisa dilihat dari pernyataan, melainkan dari konsistensi tindakan ke depan (Goffman 1959, 23–25).
Dalam tradisi NU, kiai sepuh memiliki otoritas moral yang besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa dorongan mereka berperan dalam mendorong ishlah. Namun otoritas moral berbeda dengan tata kelola kelembagaan. Jika nasihat kiai sepuh tidak diterjemahkan ke dalam aturan main yang jelas, maka konflik berpotensi berulang dalam bentuk yang berbeda (Bourdieu 1991, 72–75).
Kenegarawanan dalam konteks organisasi keagamaan besar bukan sekadar kemampuan menahan ego, tetapi juga keberanian menegakkan aturan. Jika road map diterima tanpa kejelasan batas implementasi, ia dapat menjadi preseden yang melemahkan struktur PBNU dan membuka ruang tafsir baru yang justru memperpanjang konflik (Ostrom 1990, 90–92).
Sebaliknya, jika penerimaan road map dijadikan pintu masuk untuk memperkuat konsolidasi organisasi sesuai amanat muktamar, maka tindakan Gus Yahya justru dapat dibaca sebagai langkah strategis untuk menang secara institusional. Dalam organisasi besar, mengalah secara simbolik kerap menjadi cara untuk mempertahankan stabilitas jangka panjang (March 1994, 210–212).
Konflik PBNU sejatinya bukan soal siapa menang dan siapa kalah, melainkan soal bagaimana organisasi ini dikelola di tengah kompleksitas zaman. NU hari ini tidak hanya berhadapan dengan persoalan internal, tetapi juga ekspektasi publik, relasi dengan negara, dan peran global sebagai otoritas Islam moderat (Hefner 2011, 14–17).
Karena itu, reduksi konflik ini menjadi drama personal antara Rais Aam dan Ketua Umum justru menutup persoalan yang lebih mendasar: krisis tata kelola, ketegangan antara kepemimpinan simbolik dan administratif, serta kebutuhan akan mekanisme resolusi konflik yang lebih institusional (Pierre & Peters 2000, 33–36).
Harapan bahwa ishlah ini akan mengembalikan NU ke khittah dan amanat muktamar hanya akan terwujud jika rekonsiliasi berjalan dari nurani kelembagaan, bukan sekadar kompromi citra. Jika tidak, sejarah NU menunjukkan bahwa konflik yang ditutup secara simbolik cepat atau lambat akan terbuka kembali (Coser 1956, 179–181).
Penerimaan road map oleh Gus Yahya lebih tepat dibaca sebagai kenegarawanan strategis—bukan kekalahan—namun kenegarawanan yang masih menunggu pembuktian. Apakah ia akan memperkuat PBNU atau justru menyisakan persoalan laten, sepenuhnya bergantung pada keberanian seluruh elite NU untuk menempatkan kepentingan jami’iyah dan institusi di atas segala kepentingan personal (Weber 1978, 241–243).
Dengan diadakannya pelno sebagai prasyarat Rodmap Rais Aam, sejatinya Adalah Ishlah yang tertunda. Pada pleno tersebut, Rais Aam menerima dan memberikan maaf atas “kesalahan kesalahn” gus Yahya termasuk mengembalikan struktur PBNU sebagaimana amanat Muktamar merupakan sikap kenegarawanan kedua belah pihak.
Semoga dengan Islah dan Pleno yang berakhir damai itu berangkat dari kesadaran Bersama dan kesadaran kolektif untuk kemaslahatan Jamaah dan Jamiiyah NU menuju peradaban Digital yang tidak kalah pentingnya untuk kemajuan NU ke depan. Bravo NU dan atma nan Jaya
*Penulis adalah Dosen Filsafat Digital Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya
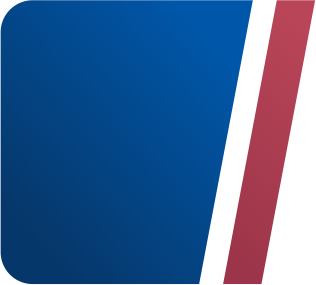 Berita terkait
Berita terkait

Nalar Hukum KPK dan Warisan Kolonial...

Berjuang Sampai Titik Darah Penghabisan: Amanat...

KPK, Nalar Silo Digital Hukum dan...

Jokowi dalam Pusaran Isu Korupsi Kuota...

Membaca Posisi Indonesia di Dewan Perdamaian...

Mantan Menag Dijerat Kasus Kuota Haji:...
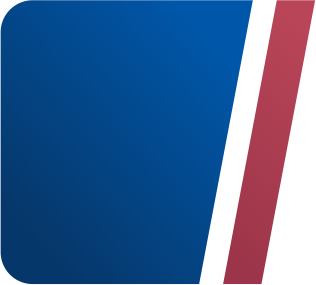 Berita Terbaru
Berita Terbaru

Penerimaan Road Map: Kekalahan atau Kenegarawanan?...

Hasto Kristiyanto: Program Makan Gratis Harus...


