Nalar Hukum KPK dan Warisan Kolonial Hukum Romawi

Oleh : Suhermanto Ja’far*
JAKARTA, BERITA SENAYAN – Penetapan kebijakan kuota haji sebagai objek perkara pidana kembali memunculkan pertanyaan mendasar: apakah hukum kita masih bekerja sebagai instrumen keadilan, atau telah berubah menjadi mesin kepatuhan prosedural yang buta konteks? Dalam kasus ini, persoalannya bukan siapa yang benar atau salah secara personal, melainkan bagaimana hukum—khususnya melalui nalar KPK—membaca kebijakan publik yang lahir dari pertimbangan kemanusiaan.
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mengadili individu, apalagi meragukan integritas personal lembaga penegak hukum. Kritik yang diajukan sepenuhnya diarahkan pada cara bernalar hukum—yakni kerangka epistemologis dan historis yang membentuk bagaimana hukum dibaca, ditafsirkan, dan diterapkan. Dalam konteks ini, istilah “warisan kolonial hukum Romawi” tidak digunakan sebagai tuduhan politik, melainkan sebagai penanda genealogis: sebuah jejak sejarah panjang tentang bagaimana hukum modern mewarisi tradisi legal yang menempatkan kekuasaan, teks, dan komando normatif di atas pertimbangan etis dan kemanusiaan. Dengan kata lain, yang diuji di sini adalah rasionalitas hukum sebagai sistem, bukan niat baik atau buruk para pelaksananya.
Karena itu, frasa “ketika kekuasaan mengalahkan kemanusiaan” harus dibaca secara konseptual, bukan emosional. Kekuasaan merujuk pada hukum yang dipahami sebagai command—tertutup dalam kodifikasi, prosedur, dan legal formalism—sebagaimana diwariskan dari tradisi Romawi dan diperkuat oleh positivisme modern. Sementara kemanusiaan merujuk pada tradisi yang lebih tua dan reflektif: etika Yunani tentang keadilan dan equity, prinsip salus populi suprema lex esto, maqāṣid al-sharī‘ah khususnya hifẓ al-nafs, serta ruang diskresi kebijakan dalam hukum administrasi. Tanpa penjelasan awal ini, kritik terhadap nalar hukum—termasuk dalam membaca kasus kebijakan haji—mudah disalahpahami sebagai serangan ideologis, padahal yang dipersoalkan justru batas rasionalitas hukum itu sendiri ketika berhadapan dengan nilai kemanusiaan.
Yunani: tradisi Kemanusiaan di atas Hukum
Dalam tradisi filsafat klasik Yunani, hukum tidak pernah berdiri sendiri. Bagi Socrates, hukum adalah ekspresi keadilan moral yang harus selalu diuji oleh rasio etis, bukan ditaati secara membabi buta (Plato 1997, Crito, 49a–50a). Plato menegaskan bahwa hukum yang tidak mengarahkan jiwa pada kebaikan bukanlah hukum yang adil (Plato 1997, Republic, 519e–520a). Aristoteles bahkan secara eksplisit memperingatkan bahaya hukum tertulis yang kaku, dan menawarkan konsep epieikeia—keadilan korektif—sebagai koreksi terhadap legalisme (Aristotle 1998, Nicomachean Ethics, V.10, 1137b–1138a).
Namun warisan etis ini mengalami pergeseran besar ketika diserap oleh Romawi. Hukum Yunani yang reflektif diinstitusionalisasi menjadi perangkat administratif imperium. Seperti dicatat Aldo Schiavone, hukum Romawi berkembang bukan untuk membentuk manusia bermoral, melainkan untuk mengatur, menertibkan, dan mengamankan kekuasaan negara (Schiavone 2012, 112–118). Di sinilah hukum mulai kehilangan watak etisnya dan menjelma sebagai sistem komando.
Stoisisme—melalui Cicero—memang masih berbicara tentang lex naturalis, tetapi dalam praktik Romawi, hukum alam justru berfungsi sebagai legitimasi hukum positif, bukan sebagai alat kritik terhadapnya (Cicero 1991, De Legibus, I.18–19). Etika tidak lagi memimpin hukum; ia sekadar menghiasinya. Inilah titik awal pemisahan hukum dari kebijaksanaan moral.
Hukum Romawi: dari Tradisi Kolonialis dan Positivisme Hukum
Warisan ini mencapai bentuk paling telanjangnya dalam positivisme hukum modern. Hans Kelsen secara tegas memisahkan hukum dari etika dan tujuan substantif keadilan. Hukum, baginya, sah sejauh prosedurnya sah—bukan sejauh ia adil atau manusiawi (Kelsen 1967, 1–5). Paradigma inilah yang secara struktural masih membayangi cara kerja banyak institusi hukum kontemporer.
Dalam konteks kasus kuota haji, pola berpikir ini tampak jelas. Kebijakan administratif yang lahir dari pertimbangan keselamatan jamaah—berdasarkan pengalaman empiris kematian akibat kepadatan ekstrem di Mina dan Arafah—dibaca semata sebagai deviasi prosedural. Diskresi kebijakan direduksi menjadi potensi tindak pidana, tanpa pembacaan serius terhadap konteks darurat dan risiko nyawa manusia.
Di sinilah terjadi apa yang dalam filsafat disebut category mistake: mencampuradukkan kebijakan publik dengan kejahatan pidana. Hukum administrasi mengenal ruang diskresi justru untuk menghadapi situasi luar biasa (Dicey 1982, 337–339). Tanpa bukti mens rea, aliran dana ilegal, atau keuntungan pribadi, pemidanaan kebijakan bukan hanya lemah secara hukum, tetapi juga problematik secara etik.
Lebih jauh, pendekatan ini bertentangan dengan prinsip etika universal yang diakui lintas tradisi. Prinsip salus populi suprema lex esto—keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi—telah lama menjadi dasar legitimasi hukum publik (Finnis 2011, 218–220). Dalam tradisi Islam, hifẓ al-nafs menempati posisi utama dalam maqāṣid al-sharī‘ah (Al-Shatibi 2005, 8–10). Mengabaikan prinsip ini berarti mereduksi hukum menjadi mekanisme administratif tanpa jiwa.
Masalahnya bukan pada integritas personal aparat, melainkan pada arsitektur nalar hukum yang digunakan. Ketika hukum hanya bertanya “apakah prosedur dilanggar?”, tetapi menolak bertanya “mengapa kebijakan itu diambil?”, maka hukum telah kehilangan dimensi rasionalitas praktisnya. Seperti dikatakan Lon Fuller, hukum tanpa tujuan moral hanya akan melahirkan kepatuhan kosong (Fuller 1969, 39–41).
Pendekatan semacam ini juga berbahaya secara sistemik. Jika kebijakan berbasis kemanusiaan dipidanakan, pejabat publik akan memilih diam daripada bertindak. Negara akan dikelola oleh birokrasi yang takut mengambil keputusan, sekalipun nyawa manusia dipertaruhkan. Ini bukan negara hukum yang kuat, melainkan negara ketakutan.
Hukum dan Kuasa: Nalar Hukum Kolonialis dalam KPK
Dalam kerangka Michel Foucault, hukum semacam ini berfungsi sebagai teknologi kekuasaan—efisien, disipliner, tetapi miskin refleksi (Foucault 1977, 26–27). Ia tidak lagi menimbang manusia sebagai subjek moral, melainkan sebagai objek regulasi. Pada titik ini, hukum sah secara formal, tetapi rapuh secara legitimasi.
Kasus kuota haji seharusnya menjadi cermin reflektif bagi KPK dan publik hukum Indonesia. Pertanyaannya bukan “siapa yang harus dihukum”, melainkan “apakah cara kita bernalar tentang hukum masih selaras dengan tujuan kemanusiaan?”. Tanpa refleksi ini, hukum akan terus benar secara prosedural, tetapi keliru secara moral.
Jika hukum ingin tetap dipercaya, ia harus berani keluar dari bayang-bayang positivisme kaku dan kembali berdialog dengan etika, kebijaksanaan, dan realitas manusia. Tanpa itu, penegakan hukum hanya akan menjadi ritual institusional—tegas di atas kertas, tetapi kosong di hadapan nurani publik.
*Penulis adalah Dosen Filsafat Digital Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya
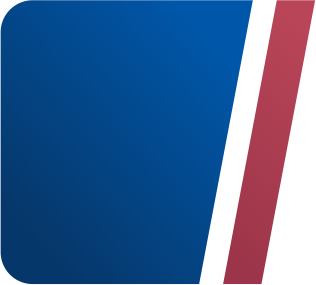 Berita terkait
Berita terkait

Penerimaan Road Map: Kekalahan atau Kenegarawanan?...

Berjuang Sampai Titik Darah Penghabisan: Amanat...

KPK, Nalar Silo Digital Hukum dan...

Jokowi dalam Pusaran Isu Korupsi Kuota...

Membaca Posisi Indonesia di Dewan Perdamaian...

Mantan Menag Dijerat Kasus Kuota Haji:...
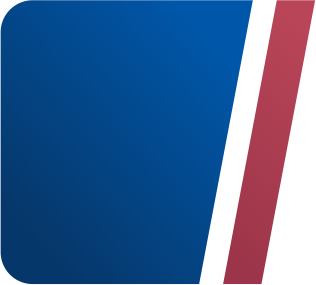 Berita Terbaru
Berita Terbaru

Penerimaan Road Map: Kekalahan atau Kenegarawanan?...

Hasto Kristiyanto: Program Makan Gratis Harus...



