Jokowi dalam Pusaran Isu Korupsi Kuota Haji

Oleh : Suhermanto Ja’far*
JAKARTA, BERITA SENAYAN – Isu pemanggilan mantan Presiden Joko Widodo dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan kuota haji kembali mencuat setelah juru bicara KPK menyatakan bahwa lembaga antikorupsi “tidak menutup kemungkinan” memanggil siapapun sebagai saksi—termasuk mantan Presiden—jika bukti awal memenuhi kebutuhan pembuktian penyidikan. Pernyataan ini, yang dilaporkan media pada 23 Januari lalu, langsung memicu gelombang opini publik yang beragam: dari yang memandangnya sebagai langkah tegas penegakan hukum, hingga yang menilai itu sekadar manuver simbolik untuk meredam kemarahan massa tanpa keberanian substantif untuk menindak secara penuh.
Pernyataan juru bicara ini seolah melemparkan bola ke publik: KPK bersikap terbuka, tetapi tidak mengambil sikap tegas kapan dan bagaimana pemanggilan akan terjadi. Di tengah desakan opini yang memaksa KPK “berani” memanggil tokoh besar, muncul pertanyaan yang jauh lebih penting dan mendasar: apakah ini merupakan bentuk independensi penegakan hukum yang objektif, atau sekadar narasi simbolik untuk menenangkan publik? Ujian besar bagi KPK bukan terletak pada durasi pemberitaan, tetapi pada kemampuan lembaga tersebut untuk berdiri di atas prinsip bahwa semua warga negara sama di hadapan hukum, tanpa terkecuali—bahkan terhadap figur mantan Presiden.
Isu dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji kembali mengguncang ruang publik. Kali ini, percakapan tidak berhenti pada level kementerian atau pejabat teknis, melainkan melebar hingga menyeret nama mantan Presiden Joko Widodo. Media sosial, kanal YouTube politik, dan grup WhatsApp ramai dengan satu pertanyaan provokatif: bisakah Presiden Jokowi dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Pertanyaan ini sah secara politik, tetapi sering kali dijawab dengan emosi, bukan dengan nalar hukum.
Masalah utama dari diskursus tersebut bukan pada keberanian bertanya, melainkan pada cara bertanya. Banyak narasi publik dibangun dari potongan informasi yang belum terverifikasi, bercampur antara opini, asumsi, dan spekulasi. Dalam iklim seperti ini, isu hukum mudah berubah menjadi arena penghakiman kolektif. Ketika rumor disamakan dengan fakta, dan viralitas dianggap bukti, maka rasionalitas hukum menjadi korban pertama.
Dalam negara hukum, prinsip paling dasar adalah presumption of innocence. Tidak ada individu—termasuk mantan presiden—yang dapat dianggap bersalah tanpa proses hukum yang sah. Jabatan tinggi tidak otomatis meniscayakan keterlibatan pidana, sebagaimana jabatan rendah tidak otomatis membebaskan dari tanggung jawab hukum. Prinsip ini sering terdistorsi ketika publik mencampuradukkan kemarahan politik dengan standar pembuktian pidana.
Secara konstitusional, Presiden memang memiliki posisi khusus. Selama menjabat, terdapat mekanisme hukum yang membatasi pemanggilan langsung oleh aparat penegak hukum. Namun, pembatasan tersebut bersifat prosedural, bukan substantif. Artinya, Presiden bukan kebal hukum, tetapi proses hukum terhadapnya tunduk pada mekanisme konstitusional yang ketat. Setelah tidak menjabat, status hukum kembali setara sebagai warga negara, tetapi tetap dengan standar pembuktian yang sama: bukti, bukan asumsi.
Dalam konteks KPK, pemanggilan seseorang—baik sebagai saksi maupun pihak terkait—harus didasarkan pada kebutuhan penyidikan yang konkret. KPK bekerja atas dasar actus reus dan mens rea: perbuatan nyata dan niat pidana. Jika dugaan korupsi terjadi di kementerian, maka fokus utama penegakan hukum adalah pada pejabat yang memiliki kewenangan operasional dan pengendalian anggaran, bukan secara otomatis pada Presiden sebagai atasan politik.
Di sinilah letak kekeliruan nalar publik yang paling sering muncul: menyamakan tanggung jawab politik dengan tanggung jawab pidana. Presiden bertanggung jawab secara politik atas pembantunya—itulah sebabnya ada reshuffle, evaluasi, dan sanksi administratif. Namun tanggung jawab politik tidak identik dengan keterlibatan kriminal. Menyamakan keduanya bukan hanya keliru, tetapi berbahaya bagi prinsip keadilan.
Kekeliruan berikutnya adalah tekanan moral agar KPK “berani” menetapkan siapa pun yang dituntut opini publik. Keberanian penegak hukum bukan diukur dari siapa yang disasar, melainkan dari konsistensinya pada hukum acara dan alat bukti. KPK yang tunduk pada tekanan viral justru kehilangan integritasnya sebagai lembaga hukum independen.
Isu kuota haji memang memiliki sensitivitas tinggi. Ia menyentuh dimensi ibadah, uang publik, dan legitimasi negara. Karena itu, penyelidikan harus dilakukan secara transparan dan menyeluruh. Namun memperluas tuduhan tanpa dasar hukum yang jelas justru berpotensi mengaburkan aktor yang benar-benar bertanggung jawab dan menggeser fokus dari substansi ke sensasi.
Uji Nyali Keberanian KPK
Pertanyaan “bisakah Presiden Jokowi dipanggil KPK?” sejatinya harus dijawab secara jujur: secara teoritis mungkin, secara praktis sangat terbatas, dan secara hukum hanya sah bila didukung bukti kuat dan relevan. Tanpa itu, wacana pemanggilan Presiden lebih mencerminkan kegelisahan politik ketimbang kebutuhan yuridis.
Di titik ini, isu sesungguhnya bukan sekadar soal Jokowi, melainkan tentang kedaulatan hukum itu sendiri. Apakah hukum ditegakkan berdasarkan prosedur dan pembuktian, ataukah digiring oleh tekanan massa dan logika media sosial? Negara hukum yang dewasa tidak bekerja berdasarkan amarah kolektif, tetapi pada disiplin institusional.
KPK juga berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, publik menuntut ketegasan. Di sisi lain, KPK dituntut menjaga akurasi hukum. Nyali keberanian KPK tidak seharusnya ditunjukkan dengan melompat jauh ke figur simbolik, tetapi dengan menuntaskan perkara secara runtut, dari aktor teknis hingga pengambil keputusan yang benar-benar dapat dibuktikan secara hukum.
Demokrasi membutuhkan pengawasan, tetapi pengawasan tanpa disiplin berpikir akan berubah menjadi trial by opinion. Kritik terhadap kekuasaan adalah hak warga negara, tetapi menghakimi tanpa proses hukum adalah bentuk ketidakadilan baru. Jika semua persoalan negara diselesaikan dengan logika “siapa paling atas, dia paling bersalah”, maka hukum berubah menjadi alat populisme.
Isu korupsi haji harus diusut tuntas, siapa pun yang terlibat. Namun ketuntasan hukum tidak identik dengan perluasan tuduhan. Justru ketelitian, kesabaran, dan konsistensi penegakan hukum adalah bentuk keberanian yang paling substansial.
Pada akhirnya, pertaruhan terbesar dalam isu ini bukanlah nama seorang mantan presiden, melainkan arah negara hukum kita. Apakah Indonesia memilih jalur keadilan berbasis bukti, atau tergelincir ke dalam politik kecurigaan tanpa batas. Di antara kedaulatan hukum dan tekanan opini, di sanalah nyali sejati KPK diuji—bukan untuk memuaskan publik, tetapi untuk menjaga martabat hukum itu sendiri.
*Penulis adalah Dosen Filsafat Digital Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya
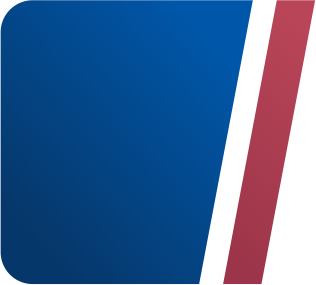 Berita terkait
Berita terkait

Penerimaan Road Map: Kekalahan atau Kenegarawanan?...

Nalar Hukum KPK dan Warisan Kolonial...

Berjuang Sampai Titik Darah Penghabisan: Amanat...

KPK, Nalar Silo Digital Hukum dan...

Membaca Posisi Indonesia di Dewan Perdamaian...

Mantan Menag Dijerat Kasus Kuota Haji:...
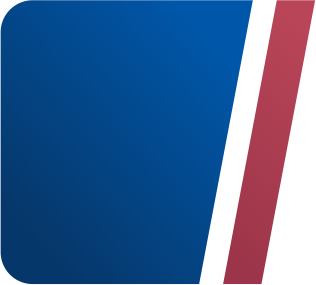 Berita Terbaru
Berita Terbaru

Penerimaan Road Map: Kekalahan atau Kenegarawanan?...

Hasto Kristiyanto: Program Makan Gratis Harus...



