Mantan Menag Dijerat Kasus Kuota Haji: Ke Mana Suara Pejabat Sruktural Kemenag?

Oleh : Suhermanto Ja’far*
JAKARTA, BERITA SENAYAN – Penetapan mantan Menteri Agama sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji telah mengguncang ruang publik. Namun, kegaduhan ini menyisakan pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah publik sungguh memahami mekanisme pengelolaan keuangan haji, atau justru sedang diseret ke dalam penyederhanaan masalah yang berbahaya bagi nalar hukum dan keadilan kebijakan?
Sejak 2019, mekanisme keuangan haji mengalami perubahan struktural yang sangat penting. Setoran jamaah haji tidak lagi masuk ke rekening Kementerian Agama, melainkan ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Lembaga ini berdiri mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bukan kepada Menteri Agama. Fakta ini seharusnya menjadi titik awal analisis, bukan diabaikan.
Dalam skema tersebut, setelah jamaah melakukan pelunasan biaya haji—yang besaran dan waktunya ditetapkan melalui keputusan pemerintah dan DPR—peran Menteri Agama bersifat administratif dan fungsional. Menteri Agama mengajukan RKA-BKOH (Rencana Kerja Anggaran Biaya Keuangan Operasional Haji) kepada BPKH untuk membiayai operasional haji, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.
Penting dicatat: RKA-BKOH bukan keputusan sepihak Menteri Agama. Dokumen tersebut berbentuk proposal anggaran yang harus mendapatkan persetujuan BPKH. Ia tidak memerlukan persetujuan DPR karena bukan anggaran negara murni, tetapi dana amanah jamaah yang dikelola secara khusus. Dengan kata lain, terdapat mekanisme checks and balances yang jelas dalam tata kelola keuangan haji.
Dalam konteks ini, tudingan pidana terhadap kebijakan haji semestinya diuji secara ketat: di mana letak actus reus dan mens rea-nya? Apakah terdapat aliran dana ke rekening pribadi? Apakah ada keputusan anggaran yang melanggar mekanisme persetujuan BPKH? Tanpa jawaban tegas atas pertanyaan ini, penetapan tersangka berisiko menjelma menjadi kriminalisasi kebijakan.
Di sinilah keganjilan paling terasa. Ketika mantan Menteri Agama—dalam hal ini Yaqut Cholil Qoumas—ditetapkan sebagai tersangka, suara institusi yang paling memahami mekanisme haji justru nyaris tak terdengar. Mana suara orang-orang Kementerian Agama? Mana penjelasan struktural dari mereka yang setiap hari mengelola urusan haji? Mana Para pejabat Kemenag yang diangkat oleh Menteri agama saat itu. Penjelasan seperti seharusnya kakanwil kemenag yang bersuara.
Pejabat Struktural Kemenag: antara Pengecut dan Aman
Lebih spesifik lagi, ke mana para Kepala Kantor Wilayah Kemenag se-Indonesia? Ke mana para Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota? Ke mana para pejabat eselon II dan III di Kemenag pusat yang selama ini berada di lingkar kebijakan haji? Mereka bukan aktor pinggiran. Mereka adalah bagian dari mesin birokrasi yang menjalankan kebijakan secara kolektif.
Ironisnya, banyak dari mereka dahulu tampil lantang dalam pujian, sanjungan, bahkan loyalitas simbolik kepada Menteri Agama saat menjabat. Namun kini, ketika kebijakan yang dijalankan secara institusional dipersoalkan secara pidana, yang muncul justru sikap diam dan cenderung menyelamatkan diri. Diam ini bukan sikap netral; ia adalah sikap politik birokrasi.
Sikap bungkam tersebut memperparah problem keadilan. Jika kebijakan dijalankan secara kolektif dalam kerangka institusi, maka pertanggungjawabannya pun harus dibaca secara struktural. Menyeret satu orang ke ruang hukum sambil membiarkan ekosistem birokrasi cuci tangan adalah bentuk penyederhanaan yang tidak jujur secara etis maupun administratif.
Penegakan hukum yang sehat seharusnya membedakan dengan tegas antara kejahatan keuangan dan diskresi kebijakan. Jika ada jual beli kuota haji, aliran dana ilegal, atau kongkalikong yang merugikan jamaah, maka siapa pun yang terlibat—pegawai, pejabat, maupun pihak swasta—wajib diadili. Tetapi jika yang dipersoalkan adalah kebijakan operasional berbasis mekanisme resmi dan pertimbangan kemanusiaan, hukum harus berhati-hati agar tidak melampaui batasnya.
Mempertanyakan Moralitas ASN Kemenag
Kasus ini harus menjadi momentum bagi Kementerian Agama untuk bersikap dewasa secara institusional. Transparansi mekanisme, penjelasan terbuka kepada publik, dan keberanian birokrasi untuk berkata jujur jauh lebih dibutuhkan daripada sikap diam yang hanya menambah kecurigaan dan ketidakpercayaan publik.
Pada akhirnya, pertanyaan “mana suara orang-orang Kemenag?” bukan sekadar gugatan moral, tetapi tuntutan akuntabilitas. Jika birokrasi keagamaan memilih bungkam ketika kebijakan yang mereka jalankan dipersoalkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nasib satu mantan menteri, melainkan kredibilitas institusi negara dalam mengelola amanah ibadah umat. Negara hukum yang sehat menuntut keberanian untuk menjelaskan, bukan sekadar keberanian untuk menghukum.
Pertanyaan paling mendasar yang justru luput dari perdebatan publik adalah soal moralitas aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Agama, termasuk di lingkungan PTKIN. Kasus kuota haji seharusnya tidak hanya dibaca sebagai persoalan hukum individual, tetapi sebagai cermin etika birokrasi. Ketika kebijakan kolektif dipersoalkan secara pidana, sementara sebagian besar aktor struktural memilih diam, publik berhak bertanya: di mana etos tanggung jawab moral ASN yang selama ini mengklaim diri sebagai penjaga nilai agama?
Budaya birokrasi Kemenag—termasuk Kementerian lain, sebagaimana banyak institusi negara lainnya—tidak steril dari problem patronase, loyalitas simbolik, dan politik kedekatan. Mekanisme pengangkatan pejabat, baik di pusat maupun di PTKIN, kerap dipersepsikan lebih ditentukan oleh kesetiaan personal ketimbang integritas dan kapasitas etik-administratif. Dalam iklim semacam ini, keberanian moral menjadi barang langka. Yang tumbuh justru sikap aman, tunduk, dan menghindari risiko—bahkan ketika kebenaran administratif dan kebijakan sebenarnya dapat dijelaskan secara rasional.
Lebih problematik lagi adalah sikap sebagian rektor PTKIN dan pejabat eselon II–III yang pada masa lalu begitu lantang memuji, menyanjung, bahkan mempromosikan kebijakan dan figur Menteri Agama. Namun, ketika figur yang sama kini berada dalam pusaran hukum, suara-suara itu mendadak lenyap. Tidak ada klarifikasi akademik, tidak ada penjelasan kelembagaan, bahkan jejak-jejak simbolik dukungan di ruang publik digital pun dihapus. Sikap ini bukan sekadar persoalan politik kampus, tetapi indikator krisis etika kepemimpinan akademik.
Diamnya para pejabat dan pimpinan PTKIN bukanlah netralitas, melainkan pilihan moral. Netralitas hanya bermakna jika disertai keberanian untuk menjelaskan kebenaran prosedural dan kebijakan secara jujur. Ketika yang terjadi justru pembiaran dan penghindaran tanggung jawab, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nasib seorang mantan menteri, tetapi martabat birokrasi keagamaan itu sendiri. Jika ASN Kemenag—yang mengelola urusan agama dan moral publik—gagal menunjukkan integritas etik di saat krisis, maka wajar jika publik mempertanyakan: agama macam apa yang sedang diajarkan oleh birokrasi negara?
Kedekatan personal, kepatuhan tanpa kritik, dan kemampuan “menyenangkan atasan” sering kali menjadi modal tak tertulis dalam jenjang karier birokrasi. Akibatnya, pejabat yang terpilih tidak dibentuk sebagai penjaga etika kebijakan, melainkan sebagai pelaksana setia yang enggan mempertanyakan arah keputusan, bahkan ketika ruang penjelasan administratif dan moral sangat dibutuhkan.
Di titik inilah persoalan keberanian pejabat eselon II dan III menjadi krusial. Ketika kebijakan yang dahulu mereka dukung dan jalankan kini dipersoalkan secara hukum, sikap diam tidak dapat lagi dibaca sebagai profesionalisme, melainkan sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab etis. Jika jabatan diraih melalui loyalitas, maka konsekuensinya adalah hilangnya keberanian untuk bersuara demi kebenaran prosedural. Pejabat yang dahulu tampil aktif dalam seremoni, narasi keberhasilan, dan pembelaan simbolik, kini memilih lenyap dari ruang publik. Pertanyaannya sederhana namun mendasar: jika bukan pada saat krisis seperti ini pejabat birokrasi berani menjelaskan kebenaran administratif, lalu kapan lagi integritas ASN akan diuji secara nyata?
*Penulis adalah Dosen Filsafat Digital Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya
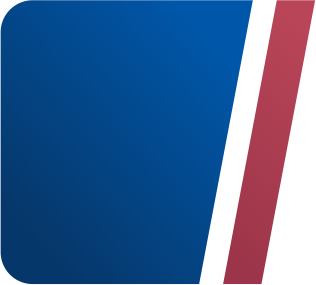 Berita terkait
Berita terkait

Penerimaan Road Map: Kekalahan atau Kenegarawanan?...

Nalar Hukum KPK dan Warisan Kolonial...

Berjuang Sampai Titik Darah Penghabisan: Amanat...

KPK, Nalar Silo Digital Hukum dan...

Jokowi dalam Pusaran Isu Korupsi Kuota...

Membaca Posisi Indonesia di Dewan Perdamaian...
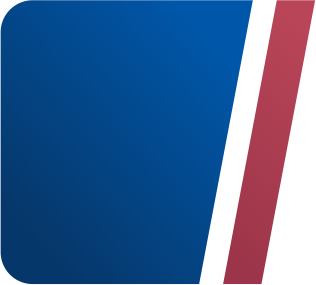 Berita Terbaru
Berita Terbaru

Penerimaan Road Map: Kekalahan atau Kenegarawanan?...

Hasto Kristiyanto: Program Makan Gratis Harus...



