Mantan Menag Dalam Pusaran Hukum KPK, Ke Mana Suara Rektor UIN?

Oleh : Suhermanto Ja’far*
Kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji yang menyeret nama mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah melampaui sekadar isu hukum. Ia kini menjadi cermin bagi dunia akademik Islam negeri, khususnya Universitas Islam Negeri (UIN) se-Indonesia. Dalam sosiologi hukum, kasus semacam ini sering menjadi stress test bagi institusi pengetahuan: apakah ia berpihak pada nalar kritis atau pada kenyamanan struktural (Habermas 1996, 321–328).
Pada masa jabatan menteri tersebut, tidak sedikit rektor UIN, pejabat kanwil Kementerian Agama, dan pimpinan lembaga pendidikan Islam yang tampil penuh puja-puji. Narasi keberhasilan dan loyalitas dibangun secara simbolik melalui seremoni dan media sosial. Fenomena ini mencerminkan apa yang oleh Pierre Bourdieu disebut sebagai symbolic capital, yakni relasi kuasa yang dibangun melalui pengakuan dan legitimasi simbolik (Bourdieu 1991, 72–83).
Namun ketika dugaan hukum mencuat, suara-suara tersebut mendadak menghilang. Dalam etika intelektual, keheningan semacam ini bukanlah netralitas. Hannah Arendt mengingatkan bahwa dalam situasi krisis moral, diam sering kali berarti penyesuaian diri dengan kekuasaan, bukan sikap objektif (Arendt 1963, 44–49).
Rektor UIN, Homo Academicus dan Loyalitas Palsu
Dalam konteks kebijakan haji, realitas yang dihadapi pemerintah kala itu sangat kompleks: negosiasi bilateral, keterbatasan kuota pasca-pandemi, tekanan sosial jamaah, serta pertimbangan keselamatan manusia. Dalam teori hukum administrasi, kebijakan publik semacam ini berada dalam wilayah discretionary power, yang secara prinsip berbeda dari tindakan kriminal (Fuller 1969, 157–164).
Di sinilah peran akademisi seharusnya hadir: menjelaskan konteks, membedakan antara policy failure dan criminal intent. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Banyak pimpinan UIN dan pejabat struktural memilih diam, bahkan menghapus jejak kedekatan simbolik mereka dengan mantan menteri. Sikap ini merefleksikan logika self-preservation birokratik, bukan integritas keilmuan (Bourdieu 1988, 89–96).
Dalam kerangka sosiologi kekuasaan, fenomena ini dapat dibaca sebagai symbolic compliance: kepatuhan diam-diam demi mempertahankan posisi dalam struktur dominan (Bourdieu 1991, 50–58). Akademisi yang seharusnya berfungsi sebagai public intellectual justru tereduksi menjadi bagian dari mekanisme kekuasaan administratif.
Keheningan ini juga berdampak pada pembentukan opini publik. Ketika tidak ada penjelasan akademik yang jernih, narasi hukum mudah berubah menjadi narasi moral dan stigma personal. Padahal, hukum pidana modern menegaskan prinsip ultimum remedium: pidana adalah jalan terakhir, bukan instrumen utama evaluasi kebijakan (Ashworth 2009, 77–84).
Rektor UIN dan Moralitas Intelektual
Diamnya para rektor UIN turut memperkuat kesan bahwa lembaga pendidikan Islam negeri kehilangan keberanian etik. Ini ironis, mengingat UIN secara normatif mengajarkan maqāṣid al-sharī‘ah—terutama ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa)—sebagai prinsip utama hukum Islam. Dalam teori hukum moral, hukum yang kehilangan dimensi kemanusiaan berpotensi menjadi represif (Fuller 1969, 210–215).
Pembelaan yang dimaksud bukan pembelaan personal atau pengingkaran hukum. Yang dibutuhkan adalah pembelaan terhadap prinsip keadilan substantif: bahwa kebijakan publik harus dibaca secara proporsional dan kolektif. Habermas menegaskan bahwa legitimasi hukum lahir dari rasionalitas prosedural dan diskursus publik yang jujur, bukan dari ketakutan institusional (Habermas 1996, 287–295).
Sikap “cari aman” atau “Pengecut” justru menunjukkan krisis kepemimpinan moral di lingkungan akademik Islam. Ketika seorang pejabat berkuasa, ia dipuja; ketika jatuh, ia ditinggalkan. Pola ini menyerupai mekanisme scapegoating, di mana individu dikorbankan untuk menjaga stabilitas simbolik institusi (Girard 1986, 21–27).
Jika UIN ingin tetap relevan sebagai penjaga moral bangsa, keberanian intelektual harus dipulihkan. Akademisi tidak boleh hanya hadir sebagai ornamen kekuasaan, tetapi sebagai penafsir kritis realitas sosial dan hukum—bahkan ketika posisi itu tidak aman (Arendt 1963, 233–238).
Pada akhirnya, kasus haji ini bukan hanya soal benar atau salah seorang mantan menteri, melainkan soal keberanian institusi pengetahuan menghadapi risiko etik. Sejarah mencatat bahwa universitas dihormati bukan karena kedekatannya dengan kekuasaan, tetapi karena keberaniannya menjaga nalar dan keadilan. Sunyi boleh jadi aman, tetapi ia jarang bermartabat (Habermas 1996, 398–402).
Keheningan para rektor UIN menjadi semakin problematik ketika publik mengingat bahwa sebagian dari mereka justru menunaikan ibadah haji pada tahun 2024—tahun yang kini dipersoalkan secara hukum dan etik dalam penyelenggaraannya. Di titik ini, persoalan bukanlah sah atau tidaknya ibadah, melainkan sensitivitas moral. Dalam etika publik, menikmati hasil dari sebuah sistem yang sedang dipersoalkan tanpa suara kritis menciptakan kesan moral disconnect antara privilese dan tanggung jawab.
Tidak ada tuduhan bahwa para rektor tersebut terlibat langsung dalam kesalahan kebijakan. Namun, etika akademik tidak berhenti pada batas legalitas. Seorang intelektual publik diukur bukan hanya dari apa yang ia lakukan, tetapi juga dari apa yang ia pilih untuk tidak katakan. Ketika para pemimpin perguruan tinggi Islam menikmati legitimasi simbolik—termasuk keberangkatan haji—di tengah badai dugaan ketidakadilan kebijakan, diam menjadi sikap yang sulit dibela secara moral.
Dalam tradisi etika Islam maupun filsafat moral modern, rasa malu (ḥayā’) adalah bagian dari integritas. Malu bukan tanda kelemahan, melainkan kesadaran diri terhadap posisi dan dampak sosial. Para rektor yang berhaji pada tahun tersebut seharusnya merasa terpanggil untuk bersuara—bukan untuk membela individu, tetapi untuk menjaga martabat institusi dan menjernihkan nalar publik. Diam mungkin aman, tetapi dalam situasi seperti ini, diam juga bisa dibaca sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab etis kolektif.
*Penulis adalah Dosen Filsafat Digital Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel
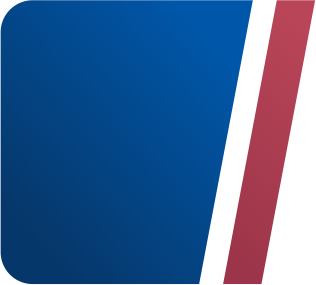 Berita terkait
Berita terkait

Paradoks Khamenei: Imam Tertinggi Revolusi Penggemar...

Obituari John Tobing Pencipta Lagu Darah...

Bahlil Orang Pande : Perspektif Tasawuf

Setahun ASR–Hugua: Membaca Arah Tata Kelola...

Runtuhnya Benteng Moral HMI : 79...

Membaca Sulawesi Tenggara Lewat Data: Perbandingan...
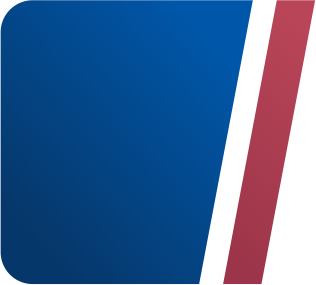 Berita Terbaru
Berita Terbaru

IDR Nilai Positif Sikap Terbuka Presiden...

Nila Yani Hardiyanti Dorong Garuda Food...



